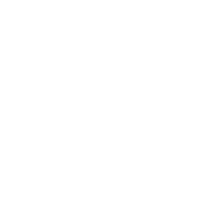Setiap Ramadan, setiap insan—khususnya umat Islam—diajarkan untuk menahan diri—bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari amarah dan perbuatan zalim. Namun, prinsip ini tampaknya tidak berlaku bagi kepolisian dalam merespons aksi protes masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI yang penuh problematika.
Gelombang aksi protes menolak pengesahan revisi UU TNI di pelbagai kota di Indonesia diwarnai dengan kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis. Amnesty International Indonesia (2025) mencatat bahwa dalam demonstrasi di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Manado, aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan, mulai dari pentungan, gas air mata, hingga meriam air, dalam upaya membubarkan massa. Sikap represif ini menunjukkan adanya pola sistematis yang membahayakan kebebasan sipil dan demokrasi.
Tindakan keras terhadap demonstran mencerminkan kecenderungan militeristik dalam penegakan hukum—terutama dengan disahkannya revisi UU TNI yang memungkinkan peran lebih luas bagi militer di jabatan sipil. Aksi represif aparat terhadap demonstran tak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis dan mahasiswa. Pelbagai tindakan, seperti pemukulan terhadap mahasiswa dan pengeroyokan terhadap seorang pengemudi ojek online yang hanya dicurigai sebagai peserta aksi.
Pola represif serupa terjadi di pelbagai kota: polisi menembakkan gas air mata dan menangkap peserta aksi di Semarang, menggunakan meriam air di Yogyakarta, melakukan pemukulan dan intimidasi terhadap mahasiswa yang ditangkap di Manado, serta di Malang mahasiswa dipukul dan direpresi secara brutal.
Peristiwa ini menandai kemunduran demokrasi Indonesia, sejalan dengan laporan Indeks Demokrasi V-Dem yang menunjukkan pergeseran menuju otokrasi elektoral. Kekerasan aparat terhadap aksi damai bertentangan dengan Konstitusi dan instrumen hukum internasional yang menjamin kebebasan berekspresi serta hak berkumpul secara damai. Tentu hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM.
Baca juga:
HAM sejatinya merupakan prinsip fundamental yang semestinya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat penegak hukum—termasuk kepolisian. Dalam penanganan demonstrasi, aparat kepolisian wajib menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul—sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 dan Pasal 21 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)—yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepolisian justru bertindak sebaliknya—menggunakan kekuatan berlebihan yang melanggar hak-hak fundamental warga negara.
Penggunaan kekerasan dalam membubarkan aksi damai tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga melanggar standar internasional terkait HAM. Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus bersifat minimal, proporsional, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah segala cara damai dilakukan. Ketika aparat justru mengedepankan pendekatan represif, negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor negara sendiri.
Jelas, tindakan brutal aparat terhadap demonstran mengindikasikan impunitas yang terus berulang dalam institusi kepolisian. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, aparat cenderung terus melakukan pelanggaran dengan dalih menjaga ketertiban umum. Padahal, dalam perspektif HAM, keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak warga negara. Negara—selaku duty bearer—berkewajiban memastikan bahwa aparat kepolisian bertindak dalam batasan hukum dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk melalui investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi protes.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, aparat kepolisian semestinya berperan sebagai pelindung masyarakat, bukan alat represi bagi kekuasaan. Ketidakmampuan mereka menahan diri dari tindakan kekerasan menunjukkan bahwa reformasi institusional masih jauh dari kata berhasil. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya kebebasan sipil yang terancam, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjunjung supremasi hukum dan HAM di tingkat global.
Baca juga:
Pun, dalam Kode Etik Aparat Penegak Hukum, serta Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa aparat mesti bertindak berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas—prinsip yang kini justru diabaikan. Jika prinsip-prinsip tersebut terus diabaikan, praktik kepolisian di Indonesia akan semakin jauh dari standar negara hukum yang demokratis, memperdalam krisis demokrasi, dan mengikis kepercayaan publik.
Ketidakpatuhan aparat terhadap hukum, penggunaan kekuatan berlebihan, serta lemahnya akuntabilitas memperkuat impunitas dan membungkam kebebasan sipil, sehingga ruang partisipasi publik semakin menyempit. Reformasi kepolisian—yang sering kali digaung-gaungkan—menjadi urgensi yang tak dapat ditunda, termasuk penguatan pengawasan independen, seperti Komnas HAM, serta peningkatan pendidikan HAM bagi aparat agar mereka bertindak sebagai pelindung masyarakat, bukan alat represi.
Jika aparat kepolisian terus gagal menahan diri dari tindakan represif, maka pertanyaannya: mengapa mereka tak ikut berpuasa dari kekerasan? Puasa dalam esensinya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengekang nafsu untuk berbuat zalim, menindas, dan melanggar hak orang lain.
Dalam hal ini, puasa semestinya berarti menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu, menegakkan hukum dengan adil, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alih-alih menahan diri, aparat justru semakin beringas, memperlihatkan bagaimana institusi ini masih jauh dari semangat reformasi yang diharapkan.
Seandainya kepolisian benar-benar berpuasa dari kekerasan, mereka akan lebih mengutamakan pendekatan dialogis dalam menghadapi aksi protes, bukan merespons dengan pentungan dan gas air mata. Mereka akan memahami bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang mesti dilindungi, bukan ancaman yang mesti ditumpas. Mereka akan menunjukkan bahwa ketertiban dan keamanan bisa dijaga tanpa mesti mengorbankan kebebasan sipil.
Puasa—dalam pengertiannya yang lebih luas—menuntut adanya refleksi dan perubahan. Jika masyarakat diharapkan menjadi lebih sabar dan bertakwa selama Ramadan, maka institusi kepolisian semestinya pun mampu menahan diri dari praktik kekerasan yang melanggar hukum dan moralitas publik.
Tanpa puasa dari kekerasan, kepolisian akan terus menjadi simbol represi, bukan pengayom masyarakat. Maka, saat masyarakat melatih diri untuk menjadi lebih baik selama Ramadan, sudah semestinya kepolisian pun melakukan hal yang sama: menahan diri, berintrospeksi, dan mengakhiri budaya kekerasan yang selama ini mengakar. (*)
Editor: Kukuh Basuki