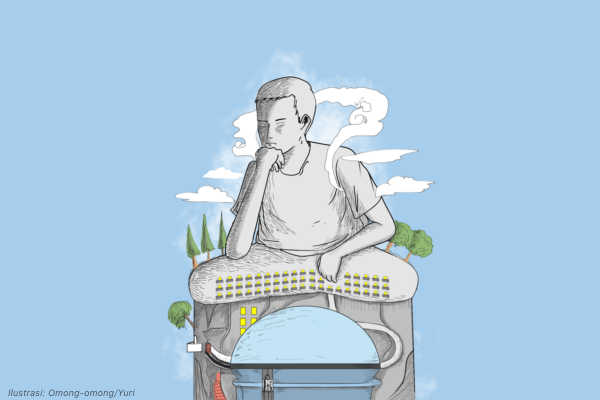Ketidaktahuan seakan telah jadi momok yang merepresentasikan kebodohan. Tidak tahu cara mengerjakan matematika, tidak tahu cara mengoperasikan kendaraan, tidak tahu mengenai materi pelajaran yang diujikan, tidak tahu akan suatu hal yang diketahui banyak orang, dan masih banyak ketidaktahuan lain yang disinonimkan sebagai kebodohan.
Namun, benarkah menjadi tidak tahu adalah sebuah kebodohan mutlak atau memang fase yang harus dilalui setiap individu agar dapat terus bergerak mencari pengetahuan?
Eric Weiner dalam memoarnya yang berjudul The Geography of Genius berkisah mengenai petualangannya menyambangi berbagai belahan dunia untuk menemukan alasan bagaimana sebuah tempat dapat melahirkan orang-orang jenius dan kejeniusan itu sendiri. Beliau mendatangi kota-kota seperti Athena, Hangzhou, Wina, Edinburgh, Florence, Kolkata, dan Silicon Valley yang terkenal telah melahirkan banyak orang-orang jenius dan kejeniusan lintas zaman.
Pada pembahasan bab pertama mengenai Athena, Eric berbincang dengan salah seorang penyair Athena modern bernama Alicia Stallings. Alicia bilang bahwa ketidaktahuan itu berkilau. Ini sama dengan yang Socrates bilang bahwa, “Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa.”
Ketidaktahuan pada dasarnya memacu kita untuk mencari tahu. Ketidaktahuan bukanlah sebuah kebodohan, melainkan suatu hal penting dalam diri seorang manusia untuk terus belajar dan berkembang.
Pada tahun 450 SM di Athena Kuno, Socrates sering berjalan-jalan di kota sembari berpikir dan berfilsafat, bertanya-tanya dalam benaknya. Orang Athena selain Socrates juga banyak yang melakukan hal ini seakan telah jadi tradisi dan budaya mereka. Bagi mereka, aktivitas fisik dan mental itu sama saja.
Akademi Plato, yang menjadi cikal bakal universitas modern, merupakan sebuah tempat kebugaran selain fasilitas intelektual. Menurut mereka, pikiran bugar yang tidak terhubung dengan tubuh bugar membuatnya tak lengkap. Sosok ideal bangsa Yunani bahkan digambarkan dalam patung thinker karya Rodin, menggambarkan lelaki perkasa yang sibuk berpikir.
Orang-orang Athena pada masa itu lebih banyak di luar rumah. Mereka mendatangi Agora—secara harfiah berarti tempat orang berkumpul. Seperti Socrates, dia selalu datang ke Agora untuk tawar menawar dengan penjual, mendengar gosip terbaru, dan membicarakan keindahan. Mereka juga sering mengadakan simposium—secara harfiah, artinya minum bersama. Di dalam simposium tersebut, mereka mengadakan jamuan makan. Namun, yang esensial adalah melakukan teka-teki intelektual, percakapan seru, melihat gadis-gadis penari, dan mendengar alunan musik.
Dari bangsa Yunani Kunolah warisan berupa dasar-dasar filsafat, drama, dan sains berasal. Bukan hanya itu, mereka juga menciptakan demokrasi. Yang menarik dari bangsa Yunani Kuno adalah kontradiksinya. Mereka orang-orang kritis yang rasional, tapi juga irasional karena memercayai dewa-dewi. Mereka membuat patung selurus penggaris, tapi jalanan dan tata letak kota tidak beraturan. Aturan mereka tegas, tapi pasar kacau balau.
Orang-orang Athena kuno juga dikenal sangat mencintai negaranya. Bahkan, ada istilah idiotes untuk mereka yang tidak berpartisipasi dalam urusan publik. Seperti kata Thucydides, “Orang yang tidak berminat pada masalah negara bukannya memikirkan urusannya sendiri, melainkan tidak mempunyai kepentingan menjadi warga Athena.” Kata idotes kemudian menjadi asal mula kata idiot yang sekarang mengalami pergeseran makna.
Orang-orang Yunani Kuno juga dinaungi ketidaktahuan. Oleh sebab itu, mereka mengadopsi berbagai ide dari bangsa lain seperti teknik pahat dan patung dari Mesir, matematika dari Babilonia, literatur dari Sumeria, dan alfabet dari Funisia. Mereka meminjam ide kepada negara asing jika mereka baik dan mencurinya jika mereka tidak berbaik hati.
Bangsa Yunani Kuno tidak malu untuk mencatut ide dari bangsa lain. Ketika mereka meminjam ide, mereka akan meng-Athena-kan ide tersebut, atau, kata Plato, ide tersebut disempurnakan. Mereka bahkan berani blak-blakan, seperti yang ditulis oleh Goethe, “Tidak mengakui seseorang adalah plagiator merupakan kesombongan bawah sadar.”
Mereka terbuka, menerima ide dan pemikiran dari luar. Mereka menerima puisi orang asing selayaknya puisi orang lokal. Mereka mengenakan pakaian asing, juga menerapkan kosakata asing. Bukan hanya itu, mereka juga menerima orang asing (metic)—sebagian sofis terkenal bukan kelahiran Athena. Warga Athena sangat menghormati mereka dengan cara memberikan karangan bunga dan biaya gratis makan seumur hidup dari anggaran publik. Ini adalah simbiosis mutualisme karena para metic juga berkontribusi secara signifikan pada negara.
Kesimpulannya adalah ketidaktahuan bukanlah sesuatu yang buruk. Ketidaktahuan itu seperti perahu yang dapat membawa kita mengarungi garangnya laut lepas. Ketidaktahuan itu berkilau, ia akan terus menerangi cakrawala pengetahuan. Yang jadi soal adalah cara kita menyikapinya—apakah kita mau bergerak atau malas-malasan?
Baca juga:
Pengetahuan dan kemajuan berkorelasi dengan keterbukaan terhadap pengalaman. Selain Yunani Kuno, Jepang juga telah membuktikan hal itu. Di era Meiji, mereka menjadi lebih terbuka dan mengalami perkembangan yang masif. Semakin besar keterbukaan Jepang, semakin pesat pula perkembangan negara itu.
Dean Simonton, profesor Psikologi dari University of California, mengatakan, “Setiap lompatan didahului oleh paparan gagasan-gagasan asing.” Jika tidak tahu, maka cari tahu, bukan diam dan malah pasrah karena tidak tahu.
Editor: Emma Amelia