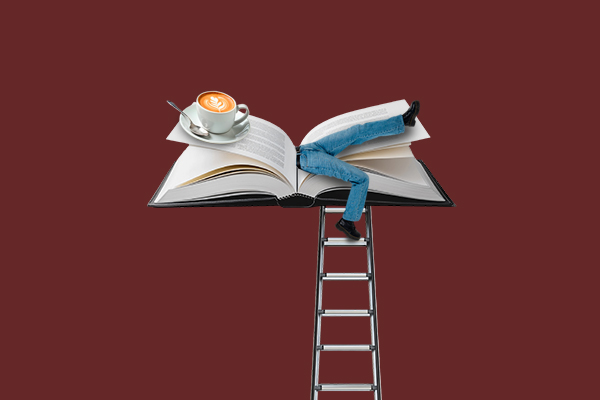Di tengah gencarnya kampanye membaca dan seruan meningkatkan budaya literasi, ironi justru tampak begitu nyata: akses terhadap bahan bacaan yang layak masih menjadi kemewahan yang sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara terus-menerus mendorong warganya agar gemar membaca, namun lalai menyediakan infrastruktur dan ekosistem yang mendukung tumbuhnya budaya literasi yang sehat dan merata.
Bagaimana mungkin kita bicara soal literasi, ketika harga buku terus meroket dan perpustakaan publik nyaris tak terurus? Buku hari ini telah menjelma menjadi komoditas mewah disandingkan dengan kebutuhan sekunder bahkan tersier. Di banyak daerah, terutama di luar pusat-pusat kota besar, toko buku nyaris tak ada, perpustakaan hanya bangunan kosong berisi buku-buku usang, dan internet sebagai alternatif akses bacaan digital pun belum menjangkau secara adil.
Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya budaya literasi bukan sekadar persoalan malas membaca, melainkan soal siapa yang diberi kesempatan untuk bisa membaca. Negara, dalam hal ini, gagal mengambil peran sebagai penyedia akses yang merata dan adil terhadap ilmu pengetahuan. Subsidi buku nyaris tidak terdengar. Penerbit lokal kesulitan bertahan karena pajak dan ongkos produksi yang tinggi. Sementara di sisi lain, acara pameran buku kerap hanya menjadi ajang konsumsi kelas menengah ke atas yang mampu membeli buku-buku baru dengan harga fantastis.
Ketimpangan ini semakin terasa ketika kita menengok pada wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana buku bukan hanya mahal tetapi juga langka. Anak-anak di sana harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk meminjam satu atau dua buku dari perpustakaan sekolah yang koleksinya terbatas dan sering kali tidak relevan.
Baca juga:
Buku pelajaran pun kerap sudah usang, tidak diperbarui sesuai kurikulum terbaru, dan dalam banyak kasus jumlahnya tidak mencukupi untuk semua siswa. Akibatnya, literasi bukanlah kebiasaan sehari-hari, melainkan sesuatu yang hanya terjadi di ruang kelas dengan materi terbatas.
Ironi lainnya tampak pada kebijakan negara yang lebih berorientasi pada produksi angka daripada substansi. Indeks literasi dijadikan kebanggaan dalam laporan resmi, sementara kualitas akses jarang dibahas mendalam.
Program “Gerakan Literasi Nasional” misalnya, sering berhenti pada slogan dan seremonial tanpa tindak lanjut nyata untuk memastikan buku murah tersedia hingga pelosok. Pemerintah bangga mengklaim bahwa telah membangun perpustakaan digital, tetapi lupa bahwa jutaan warga bahkan belum memiliki akses internet stabil, apalagi perangkat untuk membaca e-book.
Selain itu, ekosistem penerbitan buku nasional juga belum berpihak pada akses publik. Pajak kertas dan biaya distribusi yang tinggi membuat harga buku tidak pernah benar-benar ramah di kantong masyarakat berpenghasilan rendah. Distribusi buku juga terkonsentrasi di kota besar; biaya pengiriman ke daerah terpencil justru lebih mahal dari harga bukunya sendiri.
Jika negara serius ingin membangun budaya membaca, seharusnya ada kebijakan afirmatif seperti penghapusan pajak buku, subsidi ongkos distribusi, hingga penyediaan insentif bagi penerbit lokal untuk mencetak buku dengan harga terjangkau.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan sering kali lahir dari meja perumusan di pusat kekuasaan, jauh dari kenyataan hidup masyarakat yang menjadi targetnya. Literasi dipahami sebatas kemampuan teknis membaca dan menulis, bukan sebagai hak untuk mengakses pengetahuan.
Akibatnya, jurang antara mereka yang mampu membeli buku dengan mereka yang bahkan tidak pernah memegang buku semakin lebar. Kita menyebut diri sebagai bangsa besar, tetapi anak-anak di pedalaman masih harus berbagi satu buku untuk sepuluh orang.
Jika dibiarkan, ketimpangan literasi ini akan memperdalam ketidakadilan sosial. Masyarakat yang miskin akses bacaan akan kesulitan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mereka hanya menerima informasi dari televisi atau media sosial, yang sering kali sarat propaganda dan hoaks.
Tanpa kemampuan literasi yang kuat, mereka mudah dimanipulasi, baik secara politik maupun ekonomi. Dengan kata lain, kurangnya akses buku bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal demokrasi dan masa depan bangsa.
Negara seharusnya belajar dari negara lain yang berhasil meningkatkan literasi warganya bukan dengan memaksa, tetapi dengan menciptakan ekosistem yang mendukung. Di beberapa negara Skandinavia, misalnya, buku diperlakukan sebagai kebutuhan dasar. Perpustakaan berada di hampir setiap sudut kota, koleksinya selalu diperbarui, dan aksesnya gratis. Pemerintah mereka memahami bahwa investasi dalam literasi adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Indonesia bisa melakukan hal yang sama jika ada kemauan politik yang kuat. Program distribusi buku gratis ke daerah terpencil bisa menjadi prioritas. Perpustakaan desa bisa dihidupkan kembali, tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal, pegiat literasi, hingga penerbit kecil untuk mengadakan bazar buku murah atau program pinjam-buku keliling. Teknologi digital memang penting, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan infrastruktur yang memadai: internet murah, perangkat terjangkau, dan pelatihan bagi guru maupun pustakawan.
Selain itu, budaya membaca juga tidak akan tumbuh tanpa dukungan dari lingkungan sosial. Sekolah sering kali hanya menekankan literasi untuk kebutuhan ujian, bukan untuk kesenangan atau pengayaan diri. Guru terbebani administrasi, sehingga kurang waktu untuk mengajak siswa berdiskusi tentang buku di luar kurikulum. Orang tua pun banyak yang tidak terbiasa membaca di rumah, sehingga anak tidak melihat teladan. Tanpa ekosistem sosial yang mendukung, kampanye literasi akan selalu bersifat artifisial.
Baca juga:
Masalah harga buku juga harus dipecahkan secara struktural. Buku seharusnya tidak dikenakan pajak, bahkan jika perlu negara memberikan subsidi. Model distribusi alternatif seperti perpustakaan komunitas, program tukar buku, atau cetak massal untuk buku-buku populer dapat menjadi cara menekan biaya. Jika akses terhadap bacaan menjadi mudah dan murah, minat baca akan tumbuh secara alami, bukan karena dipaksa.
Pada akhirnya, membangun budaya literasi bukan hanya tentang membuat masyarakat membaca lebih banyak, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membaca.
Selama buku tetap menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu, selama perpustakaan publik tetap menjadi bangunan kosong tanpa koleksi layak, dan selama negara lebih sibuk membuat slogan ketimbang menghadirkan kebijakan nyata, maka kesenjangan literasi hanya akan semakin dalam.
Kita perlu mengubah paradigma: literasi bukan sekadar aktivitas individual, melainkan hak sosial. Buku bukan komoditas eksklusif, tetapi sarana untuk membangun bangsa. Negara yang gagal menyediakan akses bacaan yang setara adalah negara yang secara perlahan membiarkan warganya terperangkap dalam ketidaktahuan. Dalam konteks ini, kampanye membaca tanpa kebijakan akses hanyalah paradoks: menyeru rakyat untuk mencintai sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki.
Editor: Prihandini N