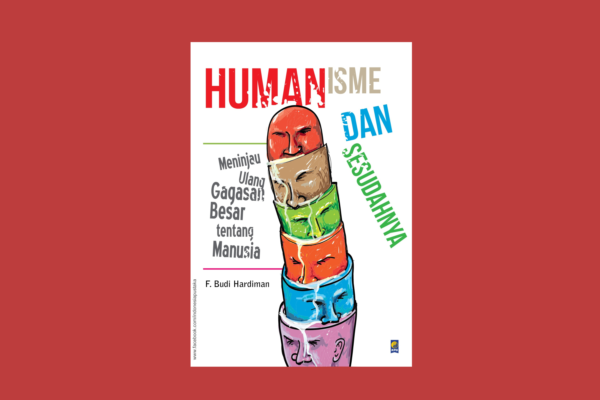Di tengah dunia yang semakin terseret arus teknologi, krisis ekologis, dan dislokasi moral global, muncul satu pertanyaan yang mengguncang fondasi peradaban modern tentang apakah gagasan “manusia” masih relevan? Pertanyaan inilah yang menjadi inti buku “Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar” karya F. Budi Hardiman, seorang filsuf Indonesia yang dikenal sebagai jembatan antara pemikiran Eropa kontemporer dan refleksi kemanusiaan Indonesia. Buku ini bukan sekadar ulasan teoretis, tetapi merupakan upaya serius untuk menimbang kembali makna menjadi manusia dalam zaman ketika batas antara manusia, mesin, dan alam kian kabur.
Budi Hardiman memulai dengan premis sederhana namun tajam yakni humanisme klasik telah kehilangan pijakannya. Ia menelusuri akar humanisme dari Renaissance yang memuliakan rasio dan martabat manusia hingga puncaknya dalam modernitas sebuah proyek besar yang percaya pada kemajuan, kebebasan, dan otonomi. Namun justru di titik inilah, kata Hardiman, humanisme mulai memunculkan benih krisisnya sendiri. Manusia yang memposisikan dirinya sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu (antropo-sentris) akhirnya menciptakan tatanan dunia yang menindas terhadap alam, terhadap sesama manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri.
Baca juga:
Di sinilah Hardiman membaca ulang kritik para pemikir poststrukturalis dan posthumanis seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Donna Haraway yang membongkar mitos subjek universal dalam humanisme Barat. Ia menunjukkan bahwa konsep manusia rasional yang diagungkan modernitas ternyata sarat dengan bias kekuasaan ras, gender, dan kelas. Humanisme ternyata bukan ruang inklusi universal, melainkan arena eksklusi yang menyisihkan pihak lain perempuan, non-Eropa, binatang, atau alam.
Namun Hardiman tidak serta-merta menolak humanisme. Ia menulis dengan kehati-hatian seorang filsuf yang sadar bahwa membuang humanisme sama berbahayanya dengan memujanya. Maka ia memilih jalan reflektif meninjau ulang, bukan menghancurkan. Dalam pendekatan inilah ia menolak dua ekstrem pertama, nostalgia pada humanisme klasik yang menutup mata dari problem modernitas kemudian, kedua, euforia posthumanisme yang ingin sepenuhnya meleburkan manusia ke dalam jaringan teknologi dan sistem non-manusia.
Kekuatan buku ini terletak pada usahanya merevisi pengertian manusia tanpa meniadakan kemanusiaan. Hardiman mengusulkan sebuah cara berpikir baru manusia bukan entitas otonom yang menguasai dunia, melainkan makhluk relasional yang eksistensinya ditentukan oleh keterkaitan dengan sesama, dengan alam, dengan teknologi, bahkan dengan yang transenden.
Dalam hal ini, ia tampak terinspirasi oleh hermeneutika dan etika dialogis Levinas maupun filsafat relasi Martin Buber. Manusia, katanya, bukan aku yang berpikir (cogito) sebagaimana didefinisikan Descartes, melainkan aku yang berelasi (homo dialogicus). Di sinilah Hardiman menegaskan bahwa humanisme baru harus lahir bukan dari dominasi, melainkan dari pengakuan terhadap kerentanan dan keterhubungan.
Gagasan ini terasa sangat relevan di tengah dunia digital yang mempertemukan sekaligus memisahkan manusia. Teknologi seakan memberi ilusi relasi tanpa kedekatan, konektivitas tanpa empati. Hardiman melihat di sinilah posthumanisme punya nilai korektif ia mengguncang keangkuhan manusia, memaksanya menyadari bahwa ia hanyalah bagian dari ekosistem luas. Namun ia juga mengingatkan bahaya baru ketika manusia sepenuhnya diserap oleh jaringan teknosains, kehilangan otonomi moral, dan menjadi data belaka dalam logika algoritma.
Salah satu bagian paling menarik dalam buku ini tentang kritik Hardiman terhadap posthumanisme ekstrem. Ia tidak menolak pembongkaran batas antara manusia dan non-manusia, tetapi menolak penolakan total terhadap subjek manusia. Menurutnya, posthumanisme yang meniadakan manusia sama nihilnya dengan humanisme yang menuhankan manusia.
Hardiman melihat kecenderungan baru dalam dunia teknologi transhumanisme dan singularitas sebagai bentuk kelanjutan dari obsesi modern atas kendali dan efisiensi, bukan pembebasan dari antroposentrisme. Manusia yang ingin menjadi Tuhan melalui kecerdasan buatan dan rekayasa genetika justru menunjukkan wajah baru dari humanisme lama yang gagal manusia yang menolak batas.
Di sinilah ia memanggil kembali pentingnya etos humanistik bukan sebagai ideologi dominasi, tetapi sebagai kesadaran moral tentang tanggung jawab dan keterbatasan. Ia menulis dengan nada kontemplatif bahwa masa depan kemanusiaan hanya dapat diselamatkan bila manusia berani menjadi manusia dengan cara yang lebih rendah hati, yakni dengan mengakui keberadaan yang lain sebagai bagian dari dirinya.
Yang membuat buku ini istimewa bukan hanya kedalaman filsafatnya, tetapi juga keberanian Hardiman mengaitkannya dengan situasi sosial dan intelektual Indonesia. Ia menyadari bahwa diskursus posthumanisme di Barat sering terjebak dalam abstraksi teknologi dan filsafat tinggi, sementara Indonesia menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih konkret tentang kemiskinan, kekerasan identitas, kerusakan lingkungan, dan korupsi moral.
Baca juga:
Dalam konteks ini, refleksi atas humanisme menjadi panggilan etis. Bagi Hardiman, humanisme baru harus berakar pada praksis sosial bukan hanya pada teori. Ia mengajak pembacanya untuk membayangkan kemanusiaan yang tidak elitis, yang memberi tempat pada mereka yang tak bersuara dalam struktur sosial minoritas, korban, dan mereka yang tersisih oleh logika kapitalisme digital. Dengan demikian, Humanisme dan Sesudahnya bukan sekadar buku filsafat, tetapi juga manifesto moral bagi zaman pasca-modern.
Sebagai karya reflektif, buku ini kaya dengan referensi lintas zaman dan disiplin dari Kant, Nietzsche, Heidegger, Foucault, hingga Habermas dan Haraway. Namun di sisi lain, padatnya muatan teoritis kadang menjadi tantangan bagi pembaca awam. Hardiman menulis dengan kedisiplinan akademik tinggi, tetapi tidak selalu dengan gaya yang komunikatif bagi khalayak umum.
Meski demikian, nilai terbesar buku ini justru terletak pada usaha sintesis yang langka untuk mempertemukan wacana filsafat kontinental Eropa dengan sensibilitas etis khas Asia. Dalam hal ini, Hardiman menunjukkan bahwa refleksi filosofis tidak pernah berhenti di Barat, melainkan harus ditafsirkan ulang sesuai konteks sosial dan spiritual tempat kita berpijak.
Kritik yang diajukan bahwa upaya membangun humanisme baru masih terasa konseptual, belum sepenuhnya menjawab bagaimana ia dapat diwujudkan dalam praksis politik, ekonomi, dan teknologi. Namun di sinilah letak kekuatan buku ini sebagai pembuka jalan, bukan penutup wacana.
Membaca Humanisme dan Sesudahnya merupakan pengalaman intelektual sekaligus eksistensial. Ia menantang kita untuk berhenti menganggap manusia sebagai kata yang sudah selesai. Di tengah ancaman kecerdasan buatan, krisis iklim, dan polarisasi sosial, buku ini mengingatkan bahwa pertanyaan paling mendesak bukanlah apa itu manusia, tetapi bagaimana kita menjadi manusia?.
Hardiman mengajak kita menyadari bahwa masa depan tidak membutuhkan manusia yang lebih kuat atau lebih cerdas, tetapi manusia yang lebih sadar akan relasi dan tanggung jawabnya. Ia menulis bukan dengan romantisme, melainkan dengan kejujuran filosofis bahwa menjadi manusia berarti belajar untuk tidak menjadi pusat dunia melainkan bagian dari jejaring kehidupan yang saling menopang.
Dengan demikian, buku ini patut dibaca tidak hanya oleh kalangan akademisi filsafat, tetapi oleh siapa pun yang sedang mencari orientasi etis di tengah dunia yang kehilangan arah. Humanisme dan Sesudahnya bukan sekadar tinjauan ulang atas gagasan besar, melainkan panggilan untuk memulihkan kemanusiaan dalam arti yang paling radikal yaitu manusia yang tidak lagi merasa satu-satunya yang penting, tetapi satu di antara yang lain. (*)
Editor: Kukuh Basuki