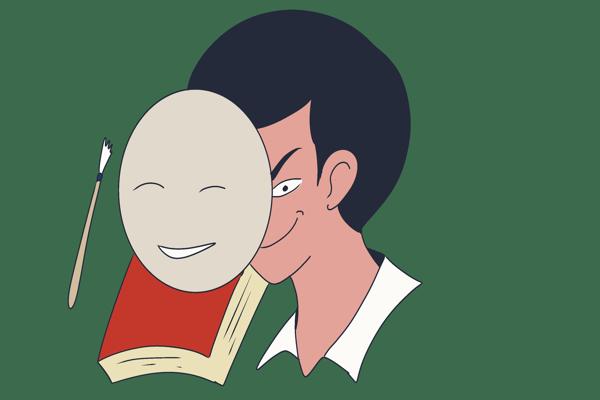Betapa janggal menyebut sebuah karya seni ngibul. Lazimnya, saat seseorang datang mengunjungi sebuah pameran karya seni, ia tidak datang dengan kecurigaan apakah karya-karya seni yang tengah dipamerkan ngibul atau tidak. Lagi pula peduli setan itu karya ngibul atau tidak, bagi beberapa pengunjung yang penting “makanan” untuk media sosialnya aman seminggu—sebulan ke depan.
Diskursus terkait ngibul atau tidaknya sebuah karya seni, mungkin, adalah hal yang asing. Kendati demikian, menurut hemat penulis, diskursus ini penting untuk diketahui, karena karya seni tidak hadir di ruang hampa. Barangkali, suatu waktu, bakal kita jumpai karya seni yang ngibul dengan tujuan seperti propaganda ideologi opresif tertentu. Oleh karena itu, penulis bakal paparkan diskursus terkait seni yang mengibuli.
Baca juga:
Referensi dari tulisan ini akan didominasi oleh tulisan Daisy Dixon berjudul Lies in Art. (Dixon, 2020) Melalui apa yang telah didiskusikan oleh Dixon, nantinya penulis akan coba lakukan analisis terhadap satu contoh karya seni di Indonesia.
Sebelum itu, di sini penulis memilih kata kibul/ngibul sebagai terjemahan dari kata lie. Penulis mafhum bahwa—sependek temuan—kata ngibul (sama seperti kata bohong) tidak sepenuhnya memuat makna dari kata lie yang mengandung niat untuk menipu/mengelabui (intent to deceive). Meskipun begitu, penulis tetap akan memakai kata ngibul. Bukan bermaksud tak tertib pada Pedoman, toh dalam konteks kehidupan sehari-hari—dengan makna yang lebih cair—kata ngibul tetap menyiratkan adanya intensi untuk mengelabui.
Krusialitas Quality Context
Bentuk seni tidak selalu hadir secara fiksional, ada kalanya seni hadir bersamaan dengan ekspektasi akan kebenaran faktual. Dalam Lies in Art, Dixon menegaskan bahwa “konteks” sangat memengaruhi apakah suatu karya seni ngibul atau tidak, sekaligus membagi dua level ngibul—surface dan deep. Secara sederhana, untuk terangkan bagaimana karya seni dapat ngibul, Dixon memberi contoh karya fotografi Yves Klein berjudul Leap into the Void (1960). Karya itu bakal ngibul jika dipajang di pameran bertajuk “Dangerous Performance Art”, dan tidak bila dipajang di pameran “Trick Photography.”
Dalam kasus di atas, konteks tajuk/tema pameran menjadi salah satu tolok ukur terjadinya pengibulan, karya fotografi Klein—yang menunjukkan ia melompat dari atap tanpa pengaman sama sekali—akan ngibul bila dipajang di pameran yang melegitimasi ekspektasi pengunjung untuk mendapatkan kebenaran. Sebab Klein tidaklah benar-benar menjatuhkan diri tanpa pengaman sebagaimana yang ditampilkan oleh karya fotografi itu, melainkan karya fotografi itu adalah hasil montase. (Dixon, 2020)
Kondisi yang melegitimasi ekspektasi pengunjung akan kebenaran suatu karya seni disebut Dixon sebagai Quality Context, istilah ini diadopsi dari Maxim of Quality milik filsuf Inggris, H. P. Grice: “Do not say what you believe to be false.” Dalam komunikasi sehari-hari, prinsip Gricean ini berfungsi sebagai truth-norm yang aktif secara otomatis; maksudnya, saat berkomunikasi kita, secara implisit, cenderung berasumsi bahwa lawan bicara tengah mengatakan sesuatu yang benar, kecuali terdapat isyarat yang menandakan sebaliknya, seperti kedipan mata, nada sarkastik, atau konteks bercanda.
Berbeda dari komunikasi sehari-hari, dalam dunia seni (the artworld), norma kebenaran itu tidak aktif secara otomatis; ia hanya akan aktif bila konteks tertentu—seperti genre atau kurasi—mengaktifkannya. (Dixon, 2020)
Ngibul dalam Seni
Dixon mengakui bahwa sukar sekali untuk mengetahui bahwa sebuah karya seni berbohong. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Quality Context tidak aktif secara default dalam dunia seni, harus ada konteks yang mengaktifkannya; konteks yang membuat audiens berhak mengekspektasikan kebenaran, sekaligus yang membuat seniman (atau kurator) percaya bahwa ia tengah berkomunikasi via karyanya dalam suatu truth-norm (Dixon, 2020).
Oleh karena itu, sebelum lebih jauh menyatakan sebuah karya seni ngibul, kita perlu memeriksa konteks yang memungkinkan terjadinya pengibulan. Dalam contoh karya fotografi Klein sebelumnya, tajuk atau tema pameranlah yang potensial mengaktifkan Quality.
Dixon menyadari bahwa sebuah karya seni memiliki layers of content yang berbeda-beda, maka, sekali pun kita berhasil menemukan indikasi konteks Quality menyala, ia tidak secara serampangan belaku begitu saja pada karya seni—yang cenderung memiliki makna berlapis-lapis.
Sebelumnya sudah disebutkan terkait pembagian dua level: surface dan deep. Level surface merujuk pada apa-apa yang secara literal tampak dari karya (visual, adegan, representasi faktual, dsb.), sedang deep adalah apa yang tengah dikomunikasikan oleh karya (pesan moral, ideologi, narasi politik, dsb.). Oleh karena itu, ketika konteks Quality ditemukan nyala, adakalanya, ia hanya berlaku pada salah satu lapisan/level, kedua level sekaligus, atau tidak sama sekali.
Sekali lagi kita kembali pada contoh Klein: katakanlah Leap into the Void ditampilkankan dalam sebuah pameran bertajuk “Dangerous Art Performances”, maka konteks kuratorial (dalam hal ini tajuk/tema) membuat audiens berhak mengekspektasikan kebenaran, Quality menjadi aktif, dan Leap into the Void telah mengibuli audiens, setidaknya, di level surface; sebab berbeda dari apa yang ditampilkan oleh karya, Klein tidak benar-benar menjatuhkan diri tanpa pengaman.
Kendati demikian, meski hasil montase, Leap into the Void sebagai sebuah karya seni tidaklah dapat dikatakan ngibul, karena karya seni tidak tunduk pada norma kebenaran, kecuali terdapat konteks yang mengaktifkannya. Tanpa adanya konteks kuratorial seperti tema “Dangerous Art Performances”, Leap into the Void tetap dipahami sebagai karya artistik atau sebuah eksperimen estetis.
Ngibul Level Deep dalam Film “Jenderal Soedirman”
Setelah mengetahui bagaimana sebuah karya seni mengibul di level surface lewat contoh Leap into the Void, sekarang penulis akan beralih kepada karya seni lain untuk menjelaskan ngibul di level deep. Film Jendral Soedirman, agaknya, dapat menjadi contoh yang tepat.
Dalam buku Suara yang Lebih Keras: Catatan dari Makam Tan Malaka, Heru Joni Putra menuliskan bahwa Tan Malaka yang ditampilkan dalam film hasil produksi Mabes TNI AD ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Film yang mengambil latar tahun 1948 saat perang gerilya ini “…merepresentasikan Tan Malaka sebagai antagonis melalui adegan pidato dengan latar belakang bendera PKI…” sekaligus “…sebagai tokoh yang bergitu berambisi menghasut orang-orang untuk melawan pemerintah.” Padahal, terang Heru, “Jika merunut pada linimasa sejarah, pada waktu itu ia (Tan Malaka) justru bersebrangan dengan PKI.” (Putra, 2021, pp. 28-29)
Begitulah deskripsi singkat tentang film Jendral Soedirman yang sekiranya dapat mendukung analisis terjadinya pengibulan. Sekarang mari masuk ke analisis.
Pertama-tama kita harus temukan dulu indikasi konteks Quality menyala. Penulis kira genre biopik-sejarah pada film sudah cukup mampu menjadi indikasi nyalanya konteks Quality: penonton berhak berekspektasi akan kebenaran, dan si kreator film lumrah diasumsikan sadar tengah mengomunikasikan kebenaran via film yang dibuatnya. Dengan demikian syarat untuk sebuah karya seni dapat ngibul terpenuhi.
Baca juga:
Jendral Soedirman telah memenuhi syarat untuk ngibul, setidaknya di level suface, meski tidak menutup kemungkinan di level deep. Pengibulan di level surface dapat kita lihat dari ketidaksesuaian apa yang ditampilkan oleh film dengan fakta sejarah, semisal adegan Tan pidato dengan bendera PKI sebagai latar belakang jelas ngibul, karena Tan di 1948 sudah tidak berafiliasi dengan PKI. Mengaitkan Tan 1948 dengan simbol PKI adalah sebuah falsehood, dan adalah sebuah bentuk pengibulan.
Untuk level deep, sebagaimana yang telah disebutkan, mempersoalkan apa pesan yang tengah dikomunikasikan oleh karya. Sekarang, kira-kira, melalui potongan adegan Tan 1948 pidato berlatar belakang bendera PKI, apa pesan yang hendak dikomunikasikan film Jendral Soedirman terhadap Tan Malaka atau komunisme secara umum? (*)
Editor: Kukuh Basuki