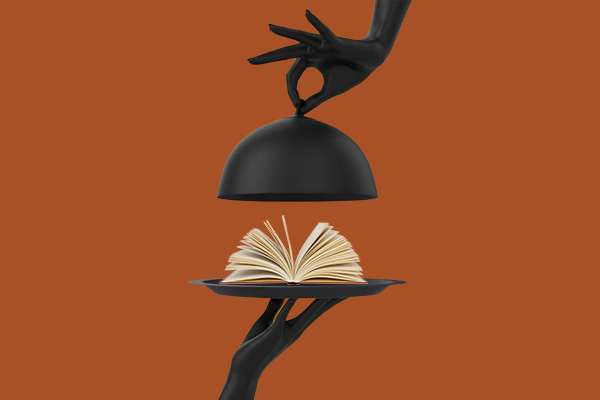Dalam beberapa tahun terakhir, “literasi” naik panggung—tiba-tiba tampak seksi sebagai kosmetik politik. Ia menjelma buzzword serbaguna: dipasang di baliho, disisipkan dalam pidato—sebagai penanda kepedulian yang pura-pura terhadap pendidikan. Banyak calon legislatif maupun eksekutif yang kini terpilih menjadikannya jargon utama sepanjang kontestasi elektoral.
Kami lelah dengan retorika minim aksi. Ungkapan yang kerap dikutip Pak Joko Widodo—walk the talk—macet di podium: tak pernah diurai, dipahami, apalagi dijalankan.
Di panggung, literasi adalah jargon; di lapangan, ia tersendat pada hal-hal paling mendasar: rak buku tak bertambah; jam perpustakaan tak ramah warga; pajak buku mencekik; guru dibebani administrasi; pengejaran kuantitas melupakan kualitas; program seremonial lebih sibuk membidik citra ketimbang pembaca.
Setiap bicara tentang literasi, data selalu konsisten menunjukkan fakta bahwa kuantitas pembaca kita memang menyedihkan, dan tentu kita belum bicara tentang kualitasnya. lantas, apa yang mesti diperbaiki? Untuk merumuskan solusi, kita perlu mengurai terlebih dahulu akar masalah literasi di Indonesia.
Pertama, ruang publik mesti jadi tempat orang bertemu teks dan sesama. Faktanya, banyak yang belum aman, belum benar benar gratis, serta belum inklusif. Di Palembang, misalnya, sejumlah taman masih diwarnai praktik pemalakan (sumbangan paksa) oleh oknum, pungutan parkir liar, serta minimnya akses bagi difabel dan anak. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas literasi sulit berakar: meriah di panggung seremoni, tetapi sepi di pertemuan warga sehari-hari.
Di negara-negara dengan ekosistem literasi kuat, ruang publik diposisikan sebagai “ruang tamu kota” tempat orang bertemu teks dan sesama dengan mandat hukum, gratis, dan inklusif, di Helsinki, Finlandia misalnya, perpustakaan pusat melebur dengan alun-alun, Lantai dasar didesain sebagai perpanjangan ruang publik untuk acara, klub baca, dan kegiatan keluarga yang mendorong orang betah di area hijau-terbuka sambil berpindah ke layanan perpustakaan.
Baca juga:
Masalah kedua, jam buka perpustakaan yang tak masuk akal. Kebiasaan baca tumbuh ketika pintu pengetahuan terbuka pada jam senggang. Namun banyak perpustakaan pemerintah masih mengikuti jam kantor—terbuka saat orang bekerja/sekolah, tutup ketika mereka punya waktu. Di beberapa kota besar mulai ada jam malam dan layanan akhir pekan, tetapi di banyak daerah perpustakaan tetap hanya buka pada jam kerja; warga terpaksa mengandalkan perpustakaan swasta yang jumlahnya terbatas di kota-kota besar.
Tugas perpustakaan adalah mengisi jeda waktu warga, bukan memaksa warga menyisihkan jeda untuk perpustakaan. Ketika jam buka selaras dengan ritme kota, kunjungan dan sirkulasi akan meningkat—dan program tidak lagi sekadar seremoni.
Ketiga, harga buku. Buku kerap kalah sebelum dibaca: harga ritel dan ongkos kirim membuat orang mundur, terutama di luar kota besar. Upah stagnan, diskon musiman tak menyentuh akar, sementara buku lokal dan terjemahan bermutu kian tak terjangkau. Tanpa intervensi yang tepat, akses ke buku menjelma kemewahan, apalagi jika meminjam dari perpustakaan pun memerlukan upaya ekstra karena jam layanan yang tidak bersahabat.
Setelah akarnya jelas—ruang yang tak aman/inklusif, jam layanan yang tak selaras, dan harga yang menghalangi—barulah “walk the talk” bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret yang terukur dan terlihat di tempat warga hidup.
Pemerintah, sejauh ini, tidak membantu apa pun selain cuap-cuap kosong. Kita pun dipaksa untuk mandiri menjaga kewarasan di tengah badai misinformasi dan perhatian yang tercerai-berai. Literasi tidak bisa tumbuh di tanah yang gersang. dan negara, alih-alih menjadi hujan yang menyuburkan, justru membiarkannya retak oleh waktu dan ketimpangan.
Literasi tak akan lahir dari seminar berbiaya tinggi atau lomba satu hari yang ditutup dengan selfie dan sertifikat. Ia butuh kehadiran yang konsisten, bukan sekadar seremoni tahunan yang berakhir di unggahan media sosial.
Sementara komunitas akar rumput berjibaku menyebarkan buku ke pelosok, para “duta literasi” sibuk mendandani panggung dengan kutipan yang tak mereka baca utuh. Jabatan simbolik dipakai sebagai pencitraan, bukan pengabdian. Mereka hadir di acara peluncuran buku, tapi tak pernah duduk mendengarkan pembacaan puisi anak desa. Mereka membagikan potret sedang memegang buku, tapi tak tahu rasanya menunggu berbulan-bulan demi sumbangan buku layak baca.
Baca juga:
Jika kerja literasi hanya dipakai untuk memoles portofolio, kita sedang menyaksikan pengkhianatan intelektual yang dibungkus senyum fotogenik. Literasi tidak butuh duta; ia butuh pelaku. Butuh tangan yang mau mengangkut kardus-kardus buku, bukan jari yang sibuk menekan shutter kamera.
Jangan heran bila akses terhadap bacaan tetap jadi kemewahan, sebab lebih banyak yang sibuk jadi wajah gerakan, daripada benar-benar bergerak. Oleh karena itu, sebelum bicara soal “Indonesia Emas 2045”, pastikan dulu apakah yang kita bangun adalah ekosistem pengetahuan atau sekadar panggung citra penuh basa-basi.
Literasi tidak butuh lebih banyak duta, tapi lebih banyak yang turun tangan, sebab membaca hari ini bukan lagi sekadar aktivitas untuk “menjadi manusia” tapi cara untuk tetap waras di tengah kekacauan informasi, tetap berpikir jernih di tengah banjir kebohongan, dan tetap kritis di tengah kultus kepatuhan.
Membaca hari ini adalah bentuk perlawanan terhadap politik yang malas berpikir, terhadap algoritma yang mereduksi kenyataan, terhadap sistem yang ingin kita sibuk bekerja tapi enggan kita berpikir.
Maka dari itu, ketika para pejabat masih sibuk mencuap tentang literasi dari balik podium, kita sudah lama tahu bahwa suara tanpa langkah hanyalah gema kosong. Dan membaca, hari ini, bukan sekadar kegiatan tapi pilihan sadar untuk tidak tunduk.
Ketika negara gagal mengatur harga, kita akan berbagi buku sebisanya. Ketika kampanye literasi hanya jadi ajang foto bersama, kita akan menulis ulang sejarah dari pinggir dengan kesabaran, dengan suara, dan dengan kalimat yang tak bisa dibungkam.
Siapa pun yang takut pada buku, sesungguhnya sedang takut pada kemungkinan manusia untuk berpikir. Dan kita, di sisi yang membaca, tidak akan berhenti.
Editor: Prihandini N