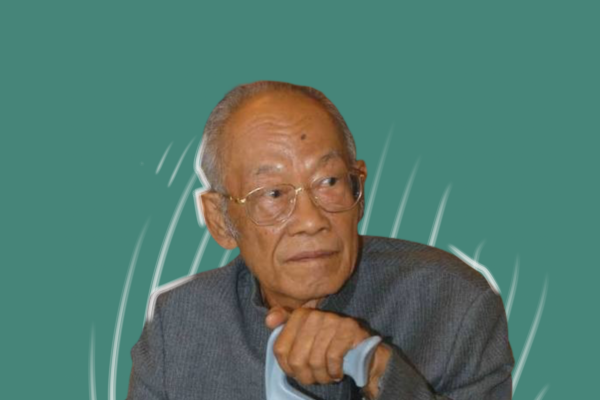Kelindan lapar yang diderita Pramoedya bersama ribuan tapol kekerasan antikomunis 1965–1966 lainnya menuntut penguakan. Esai ini turut memeringati nyala #SeabadPram yang mungkin padam kelak, tapi tidak hari ini.
Kelaparan, dalam arti sebenarnya, selalu mengiring para tahanan politik (tapol) kekerasan antikomunis 1965–1966, termasuk Pramoedya Ananta Toer. Namun, Pram menaruh hormat kepada sesama tapol karena berani “menentang lapar”: memakan cicak, lintah, kadal, tikus kakus, ular —hal yang tak lazim dikonsumsi di masa normal. Apalagi, sumber pangan tadi diolah dengan cara begitu minim. Tak jarang Pram melihat kawannya menelan cicak, atau pun anak tikus. Semua itu dilakukan semata agar nyala hidup tetap nyalang. Namun, karena kelaparan itu, tak sedikit pula yang gugur.
Penahanan inkonstitusi Pram karena diduga terlibat Gerakan 30 September 1965, yang diikuti pembersihan golongan kiri pada 1965–1966. Hingga lebih dari separuh abad, fakta kekerasan itu tetap teronggok di bawah karpet kuasa. Jess Melvin, sejarawan Australia National University dalam Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal (2022) membabar bila rantai komando militer berperan vital dalam skenario penumpasan. Melvin bahkan mengategorikan kekerasan antikomunis itu sebagai “genosida” yang didalangi Harto.
Beralasan bila Pram berkata Orde Baru, singgasana Harto yang dibangun di atas bau anyir darah itu, sebagai “kekuasaan yang dibangun dengan pembunuhan massal selamanya menjadi sistem yang lebih sibuk membenahi nurani sendiri”. Maka “jangan harap urusan makanmu beres.” (Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (NSSB) I, h. 49)
Penahanan para tapol tak ubahnya pelucutan kemerdekaan, karena tuduhan yang diajukan kepada mereka tidak berdasar. Seorang tentara di penjara Salemba pernah berujar bahwa para tapol “Tak punya hak apa-apa selain bernafas” (NSSB I, h. 3). Sejak itu, kelaparan selalu mengiring tapol. Semula, para tapol ini mendekam di Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba (1965–1969), diangkut ke Nusakambangan (Juli–Agustus 1969), lalu diasingkan ke Pulau Buru (1969–1979). Pram sendiri baru “bebas” pada Desember 1979.
Baca juga:
Selama ditahan di Salemba, para keluarga tapol masih bisa mengirim makanan, meski acap tak utuh lagi. Makanan itu dibagi bersama, untuk dana umum seluruh penjara, atau dikutip para sipir. Keluarga tapol itu tak tega membiarkan sanak mereka mati kelaparan. Jadinya, tetap saja para tapol ini berkarib dengan rasa lapar, kelaparan yang dibikin oleh Negara pula. Lapar dalam kurungan tembok tebal, dalam amatan Pram saat itu, lebih mematikan ketimbang lapar di masa Jepang (NSBB I, p. 131).
Pengasingan para tapol dari Jawa ke Pulau Buru dimulai pada 1969. Mereka transit dulu di Penjara Nusakambangan di lepas pantai Cilacap. Pangan yang tak memadai terus-menerus menjadi momok kesehatan para tapol. Berikut kondisi beberapa tapol seperti amatan Pram kala di Nusakambangan:
“Matanya kelihatan besar melotot, terlalu besar, tapi tak semua yang dilihatnya nampak jelas, kulitnya kering, dan perbukuan-perbukuannya seperti tinju kosong, menolehnya tidak menentu dan lamban, sedang pandangan matanya tertebar ke mana-mana tanpa tujuan pasti. Pemandangan biasa di masa pendudukan Jepang memang, dan pemandangan biasa dalam kehidupan tapol RI kurun ini.” (NSSB I, h. 3)
Kelaparan yang mesti ditanggung para tapol ini membuat mereka merenggut daun-daun bluntas bersaput debu dan mengganyangnya mentah tanpa dicuci. Tikus gemuk, cicak, bonggol pisang, batang pepaya bahkan sate lintah pun tandas demi lambung yang sedikit terisi. Apa boleh bikin.
Agar Hidup tak Punah
Ke mana lesapnya pengetahuan kita tentang seluruh kekerasan ini? Ditelan propaganda Orde Baru. Sekian tahun pikiran publik dikaburkan rezim Harto. Pemerintahan otoriter ini memang menyebut Buru sebagai tempat pemanfaatan (tefaat) dan instalasi rehabilitasi (inrehab). Mudah kita ajukan tanya: dimanfaatkan untuk dan rehabilitasi dari apa?
Asvi Warman Adam, sejarawan, dalam satu esai dalam Kejahatan Tanpa Hukuman (2021) menulis selama di Buru, para tapol dimobilisasi untuk bekerja “membangun” paksa pulau itu: 10 jam sehari, di bawah pengawasan pasukan bersenjata. Kerja wajib ini juga inkonstitusi, sebab ditetapkan bukan melalui pengadilan yang kompeten.
Kerja paksa selama di Buru oleh para tapol diawali dengan, menukil Asvi, “pemindahan paksa, pembuangan dan pengusiran, penganiayaan, serta berlangsung dalam kondisi ketersediaan pangan dan fasilitas kesehatan yang minim yang mengakibatkan kelaparan dan penyakit“. Inilah yang Pram sebut bahwa “di tangan penjahat, jatah makan dan gizi pun bisa jadi alat menumpas.”
Di Pulau Buru, para tapol dipaksa tinggal di savana “yang kedekut ini [dan] terserah pada intuisi untuk hidup.” Dan bagi Pram, “kekuasaan yang menahan dan menghukumnyalah yang mestinya menjamin kelangsungan hidup yang ditahan dan dihukum” (NSSB I, h. 69). “Kelangsungan hidup” ini tentu juga soal pangan, kebutuhan mendasar bagi saban makhluk.
Djamal Marsudi dalam Laporan Pertama dari Pulau Buru (1971) mengeklaim di sana para tapol dijamin pangannya, peralatan pertanian, bibit dan sebagainya, hingga mereka bisa berhasil dari usaha sendiri. Bantuan pangan, misalnya: Beras 15 kilogram 2 ons, ikan asin 1,5 kg, dan minyak tanah 3 liter —semua/bulan. Apakah itu cukup? Persoalannya bukan itu.
Karena mobilisasi pangan di Buru mengandalkan aliran sungai, keadaannya memburuk seiring muka air surut. Apa boleh buat, beberapa tapol mesti mengangkut berkwintal beras dalam jarak 3,5 kilometer. Sementara, kualitas dan kuantitas pangan juga cepat susut. Para tapol ini juga kebanyakan orang kota yang tak terbiasa bekerja fisik. Banyak di antara mereka adalah pekerja seni, pengajar di kampus, ilmuwan, penulis dan semacamnya. Namun di Pulau Buru, mereka mesti membersihkan hutan, mengolah ladang, menanam tanaman pangan, dan sebagainya—ya, kerja paksa.
Begitu juga Pram. Karena ia kerja terlalu berat dan hujan kerap turun, dengan cepat kesehatan dan berat badannya anjlok. Perutnya mulai dibobol penyakit; tiap usai makan dia buru-buru ke jamban. Untuk sekadar bangkit dari jongkok usai berak saja ia kepayahan. Ditambah ia seorang pemilih pangan. Kondisi paling minimum bagi seorang penulis.
“Boleh jadi berat badanku telah hilang sepuluh kilogram. Kekurusanku melebihi di masa pendudukan Jepang yang waktu itu sudah aku anggap sebagai titik terdalam.” (NSSB I, h. 64) Sementara kesehatannya memburuk, jatah bulgur pun ikutan merosot. Bulgur itu kadang bergumpal, berjamur, tak jarang juga bercampur dengan lempeng karat kapal.
Baca juga:
Dalam kondisi pangan yang sudah sedemikian buruk, Pram paksa dirinya untuk “dapat melahap sembarang daging” mengikuti kawan-kawannya. Ia pun menyantap “segala macam daging yang disediakan bumi ini”. Ia mulai makan tikus saat membersihkan alang-alang, telur kadal, hingga ular, katanya “daging itu menjadi lebih enak bila digoreng dengan lemaknya sendiri” (NSSB I, p. 67). Tampaknya, hanya daging anjing liar dan ulat sagu mentah yang masih bikin Pram gentar. Semua itu “untuk tidak punah karena turunnya gizi, kwalitas dan kwantitas makanan […] protein hewani penghuni pada[ng –sic.] rumput harus dimanfaatkan.” (NSSB I, h. 66)
Di sisi lain, apa yang didatangkan pemerintah ketika kelaparan melanda para tapol? Tulis Pram, justru yang hampir saban lebaran datang adalah ulama dari “dunia bebas yang mengajari mereka tentang berpuasa menahan lapar dan nafsu” (NSSB I, h. 4). Bayangkan, mengajari arti lapar pada mereka yang bahkan mendapat makanan layak pun tak pernah!
Setelah panen huma yang berlimpah, akhirnya mereka sanggup makan nasi, singkong pun sudah mulai berumbi. Sejauh urusan hidrat arang, persediaan aman; mereka tak lagi perlu memangkur batang aren dan dibuat kue lempeng, yang saat memakannya harus sembari menyemburkan sepah (NSSB I, h. 68); mereka juga masih sempat mengail ikan. Hasil panen mereka surplus, dan dapat membantu unit tefaat lain.
Namun, bukankah makan hanya syarat dasar agar makhluk bisa hidup? “Ada banyak syarat lain yang harus dipenuhi untuk membuat orang menjadi manusia dengan segala harkat dan kehormatannya. Sejarah umat manusia sejak dapat dikenal adalah rangkaian pergulatan untuk itu,” tulis Pram. (NSSB I, h. 68)
Pram memang telah akrab dengan frasa lapar —dalam arti kias atau harfiah. Dalam larik-larik Nyanyi Seorang Bisu, memoar yang ia susun selama di Buru, Pram mengenang dirinya lahir saat Jawa masih terpasung penjajah, kelaparan bisa diwajarkan. Meskipun tak menyenangkan, rasa lapar perlu diterima sebagai sahabat. Namun tidak demikian halnya bila kelaparan terjadi di alam merdeka, apalagi akibat ketidakbecusan penguasa. “Di dunia peradaban kekuasaan yang menahan harus memberi makan tahanannya. Dalam masa Orba sedapat mungkin tahanan harus hidup dari keluarganya atau usahanya sendiri,” tulisnya.
Rasa jijik tak pernah hinggapi Pram dan para tapol kala mengganyang pangan tambahan di Buru. Baginya itu adalah tindakan yang kelewat berani—keberanian menentang lapar telah menjelma kepahlawanan itu sendiri! Apalagi, usai penghentian kiriman jatah makan dari Pemerintah. Ini jelas pesan: para tapol mesti bertahan dari intuisi untuk hidup. “Dan kelaparan itu sendiri apakah bedanya antara pembunuhan sistematis dengan kerakusan para pejabat?” Padahal, segala persoalan itu tak perlu terjadi dan menyebabkan Pemerintah berpusing ria memikirkan biaya bagaimana para tapol membangun Buru. Andaikata para tapol terbukti bersalah di hadapan pengadilan kompetan, beri hukuman yang setimpal. Bila tidak, seperti ucapan Pram:
“Gampang saja: bebaskan mereka. Itu adalah pembangunan manusia Indonesia yang lebih baik. Dan ini adalah jalan yang sangat gampang.” Tapi, kita tahu bukan itu yang Orde Baru lakukan. (*)
Editor: Kukuh Basuki