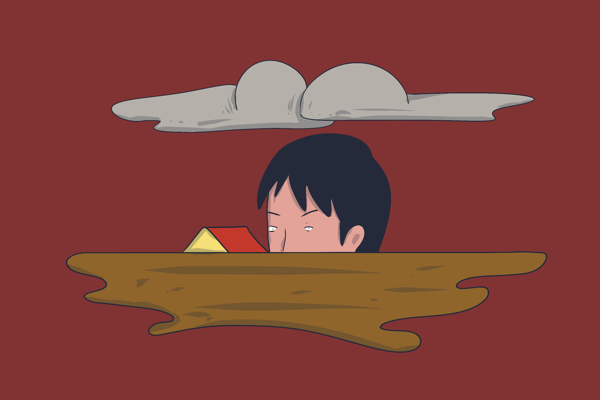Ada sesuatu yang selalu terasa janggal setiap kali bencana melanda. Kita menyaksikan banjir besar yang membawa batang-batang kayu sebesar tiang listrik menghantam pemukiman, lalu para pejabat datang dengan mengenakan pelampung.
Mungkin karena lebih mudah menyelamatkan tubuh yang hanyut daripada menyelamatkan kebijakan yang salah arah. Padahal, kayu-kayu yang hanyut itu adalah pesan paling jujur dari hutan yang telah lama dirusak secara perlahan. Khusunya di Sumatera Utara.
Dalam konteks ini, peringatan dari lembaga internasional sebenarnya sudah lama terdengar. Hutan di Sumatera telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan nama Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) sejak 2004. Namun, maraknya penebangan liar dan perambahan kawasan sejak 2011 membuat UNESCO menandai kawasan tersebut sebagai “dalam bahaya”.
Baca juga:
TRHS sendiri mencakup tiga taman nasional yang berjauhan Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan dengan luas keseluruhan 2.595.124 hektar, membentang dari Aceh hingga Lampung. Ini adalah salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara, sehingga kerusakannya bukan sekadar persoalan lokal, tetapi ancaman global.
Sementara itu, dunia sendiri sedang berada di ujung napas. Global carbon budget yang tersisa hanyalah sekitar 250 gigaton CO₂ untuk menahan suhu bumi tetap di bawah 1,5°C. Dengan laju emisi saat ini, ruang itu akan habis dalam waktu kurang dari enam tahun.
Jika ambang batas ini terlampaui, dunia akan menghadapi banjir rob ekstrem, kekeringan berkepanjangan, hingga hilangnya 14% spesies terestrial dalam beberapa dekade mendatang. Dampaknya bukan hanya ekologis, Bank Dunia memperkirakan 143 juta orang di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Amerika Latin akan terdorong bermigrasi internal akibat tekanan iklim pada 2050.
Peringatan-peringatan ini sebenarnya sudah menjadi bahasa diplomasi global. Kita memiliki Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dan Agenda 2030 SDGs yang menegaskan bahwa diplomasi hijau bukan sekadar agenda lingkungan melainkan menyangkut keamanan, stabilitas sosial, dan kemanusiaan.
Namun melihat apa yang terjadi di Sumatera Utara, semua komitmen itu tampak hanya hidup di ruang konferensi internasional, bukan pada saat arus air deras mengetuk pintu rumah warga.
Indonesia selalu bangga menyebut dirinya “paru-paru tropis dunia”, dengan kawasan hutan seluas 125,9 juta hektare. Pertanyaannya kini sederhana, siapa yang sebenarnya menebang paru-paru itu? Dan siapa yang paling diuntungkan dari pembongkarannya?
Akar Bencana yang Terus Diabaikan
Menurut Global Forest Watch dan Greenpeace, Indonesia kehilangan 292.000 hektare hutan primer tropis pada 2023. Hal itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan laju kehilangan hutan tercepat di dunia. Sebagian besar kerusakan terjadi di Papua dan Kalimantan tetapi Sumatra, termasuk Sumatra Utara, sudah jauh lebih dulu porak-poranda oleh konsesi kebun, tambang, dan penebangan “legal tapi merusak”. Tidak heran bila setiap banjir bandang membawa kayu gelondongan.
Negara tampaknya lebih siap membongkar hutan daripada menjaga ekosistem. Indonesia termasuk dalam sepuluh besar penyumbang emisi karbon global, dengan total emisi sekitar 1,04 gigaton CO₂e pada 2022. Namun anehnya, ketika bencana datang, penjelasan resmi selalu kembali ke narasi lama: “cuaca ekstrem”, “musibah”, “takdir”. Padahal deforestasi adalah ekstrem yang sebenarnya.
Baca juga:
Padahal di atas kertas, negara mengaku siap berubah. Indonesia telah menyusun Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), dengan target ambisius FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.
Ada tiga jalur strategi iklim: CPOS, TRNS, dan LCCP yang terakhir diklaim paling sesuai dengan target 1,5°C. Namun strategi tidak akan berarti tanpa sinergi lintas lembaga, tanpa pengawasan daerah, tanpa keberanian menegakkan hukum, dan tanpa menghentikan industri yang terus memperlakukan hutan sebagai halaman belakang tempat izin ditebar dan untung ditebang.
Dan setiap kali gambar banjir beredar, anak kecil digendong, rumah terendam, jembatan putus negara kembali memainkan lakon lama: hadir sebagai ‘penyelamat’. Padahal sudah jelas, negara adalah bagian dari penyebabnya. Kita tidak pernah benar-benar siap menghadapi bencana karena kita tidak pernah benar-benar siap menjaga hutan. Kita hanya siap membongkarnya.
Entah sampai kapan di Sumatera Utara harus hidup dengan perasaan bahwa setiap tetes hujan adalah ancaman. Tetapi selama negara hanya hadir setelah kayu menghantam rumah warga, bukan sebelum hutan ditebang, tampaknya banjir akan selalu menjadi tamu tetap. Dan kita akan terus menonton ulang drama yang sama: alam marah, rakyat tenggelam, pemerintah datang membawa pelampung lalu pulang sebelum air surut. (*)
Editor: Kukuh Basuki