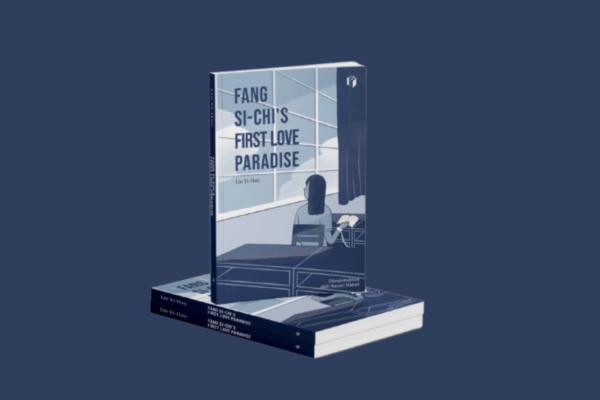Fang Si-Chi baru berusia 13 tahun ketika Lee Guo-Hua memerkosanya untuk pertama kali. Pemerkosaan baru berhenti ketika Si-Chi berusia 18 tahun— di sebuah motel. Itu kali terakhir kriminalitas Lee tercatat di buku harian Si-Chi. Sebelum kesadaran sepenuhnya meninggalkan tubuh dan jiwa perempuan muda tersebut.
Ketika menutup halaman terakhir Fang Si-Chi’s First Love Paradise, insting pertama saya adalah menjelajahi e-reader dan mencari koleksi buku apapun yang dapat membantu meregulasi emosi yang tidak terjelaskan.
Marah? Tentu. Sedih? Tidak terkecuali. Ngeri? Pasti. Tapi, bingung? Itu bukanlah kata yang seharusnya digunakan mendeskripsikan novel pertama dan terakhir Lin Yi-Han.
‘Bingung’ yang dimaksud merujuk pada sebuah sentimen ketika cerita Fang Si-Chi terasa jauh, sekaligus dekat. Asing, tapi juga akrab. Ada berapa banyak korban pemikatan seksual (grooming) di luar sana?
Baca juga:
Apa yang terjadi dalam kepala korban kekerasan seksual tidak banyak tergali karena berbagai alasan dan pertimbangan. Oleh karena itu, keputusan penulis untuk mengeksplorasi bagian paling menyakitkan ini bukan hanya bentuk keberanian, tetapi juga teriakan bahwa kekerasan seksual di kalangan anak bawah umur tidak pernah sepele dan akan selalu bersifat struktural.
Alih-alih menuturkan kisah secara kronologis, Lin Yi-Han memilih alur maju mundur, ulak-alik antara tokoh-tokoh sentral. Pembaca tidak hanya diajak untuk marah, tapi juga muak, sekaligus jijik, demi keadilan yang selayaknya diterima Fang Si-Chi.
Berlindung di Balik Rak Buku
Penurunan angka kelahiran tidak menghentikan laju pertumbuhan kursus bimbingan belajar (cram school) di Taiwan. Tren ini mengalami kenaikan signifikan hingga 2025. Persaingan sengit di sekolah dirasa belum cukup bagi generasi orang tua baru di negara itu. Mereka mendesak anak-anak untuk menjadi mesin ujian yang hari-harinya dipenuhi soal dan perlombaan nilai.
Kondisi pendidikan di Taiwan inilah yang jadi pijakan Lin Yi-Han untuk memulai cerita mengenai tersistematisasinya kekerasan seksual yang terjadi pada Si-Chi.
Lee Guo-Hua adalah tutor sebuah kursus bimbingan belajar. Kariernya melejit, sehingga wajar banyak calon murid mengantre. Dengan kuasa sebagai guru bimbingan, Lee memiliki berbagai keuntungan untuk mendekati para siswi.
Fenomena kursus bimbingan belajar secara tidak langsung mengubah cara pengetahuan diraih. Tidak lagi berada di ruang diskusi setara dan terbuka, ilmu didapatkan melalui cara-cara robotik yang kaku, tertutup, sekaligus berorientasi pada hasil.
Kesibukan anak-anak belajar bolak-balik dari sekolah ke kursus bimbingan membuat mereka teralienasi dengan orang tua. Celah ini yang digunakan Lee untuk membangun basis predatornya. Wawasan ihwal dunia sastra ia manfaatkan untuk memikat Si-Chi yang tengah berada di usia ketika segala tindak-tanduk digerakkan rasa penasaran.
Si-Chi terpikat pada sosok Lee karena pesona pria berusia lebih dari 40 tahun itu mencerminkan daya intelektual— hal baru di luar rutinitas pendidikan formal yang biasa ia temui. Ketertarikan Si-Chi terhadap sastra dunia sedari kecil yang diperlihatkan dalam penggambaran rak buku di rumah serta caranya menyitir para sastrawan, dengan cepat direduksi. Di mata Lee, minat tersebut semu dan hanya dianggap sebagai upaya Si-Chi untuk keluar dari dunia kanak-kanaknya.
Di sisi lain, minat Si-Chi itu dipergunakan sebagai sela untuk memasukkan dirinya secara perlahan-lahan. ““Bagaimana kalau aku tunjukkan koleksi buku-buku pemenang penghargaan Nobel?” tanya Guru Lee kepada kedua gadis itu dengan lembut.
Dialog Lee di atas tidak hanya mengisyaratkan tipu daya yang menjebak Si-Chi jadi korban pemerkosaan. Percakapan tersebut menunjukkan betapa korupnya seorang individu ketika menggenggam otoritas tertentu.
Lee tanpa malu merapal empat ajaran: kelembutan, kebaikan hati, kehormatan, dan kerendahan hati, saat memerkosa para korban (ya, Si-Chi bukan satu-satunya). Seolah ia tidak sadar dengan kejahatan yang ia lakukan. Seakan memikat perempuan muda adalah ‘bayaran’ atas kerja kerasnya menyelamatkan nilai anak-anak agar bisa masuk ke sekolah terbaik di Taiwan.
Jika belum cukup mengerikan, Lee bahkan tidak bisa melepaskan pandangan kotor terhadap anak perempuannya sendiri yang belum lagi remaja.
Mengikat Rasa Bersalah Korban
“Ketika menemukan kembali suaraku, aku minta maaf kepadanya. Ada semacam rasa bersalah, seakan-akan aku tidak mengerjakan tugas sekolahku sampai selesai, meskipun itu bukan PR-ku…. Aku tahu, setiap kali tidak tahu bagaimana harus menjawab perkataan orang dewasa, lebih baik mengiyakan mereka saja,” tulis Si-Chi dalam salah satu lembar buku hariannya.
Jika tidak dipahami secara perlahan, pembaca rawan terjebak dalam memandang Si-Chi jatuh cinta dengan pemerkosanya. Misal melalui dialog semacam, “Apakah Guru mencintaiku? Guru, apakah kamu mencintai istrimu?”
Percakapan semacam itu justru menunjukkan konsekuensi dari dunia yang masih patriarkis. Korbanlah yang harus menanggung beban rasa bersalah sekaligus perasaan tidak lagi berharga. Justru lebih mudah bagi Lee sebagai pelaku untuk mendapatkan pengampunan dari orang-orang terdekat dan masyarakat luas.
Perangkat pengetahuan digunakan Lee untuk menegaskan relasi kuasa antara dirinya dengan Si-Chi. Sebagai individu dengan previlese besar (pria, lebih tua, tutor terkenal, digambarkan pintar), Lee mengikat Si-Chi dalam pertalian tak seimbang.
Upaya Si-Chi dan korban lain untuk menganggap hubungan dengan Lee seimbang layaknya sepasang kekasih berangkat dari konsep pertahanan diri. Si-Chi dan korban lain tidak bisa dengan mudah lepas dari Lee karena yakin mereka tidak lagi punya ruang untuk angkat bicara maupun kesempatan untuk diterima kembali oleh masyarakat.
Pandangan bahwa mereka bukan lagi perempuan “utuh”, “bersih”, “baik”, dan “sempurna”, merasuki korban saat melihat diri sendiri.
Mungkin ini bayaran atas hidup di dunia misoginis. Perempuan terbiasa merasa berdosa atas tindakan pelaku. Menempatkan cerita Fang Si-Chi sebagai fenomena alih-alih masalah struktural sama artinya dengan mengerdilkan rasa sakit para korban.
Bak Cermin Dibelah Dua
Fang Si-Chi bukanlah satu-satunya pusat cerita. Ada Yi-Ting yang mengagumi Lee dan cemburu dengan hubungan Si-Chi dan lelaki itu. Serta, Iwen— perempuan muda dan pintar yang jadi korban kekerasan dari suaminya. Ketiganya tinggal di satu griya tawang yang sama.
Lahir sebagai perempuan adalah hal aneh. Nyaris seperti momen kosmis ketika saya merasa bisa terhubung dengan perempuan lain, terutama jika menyangkut kejadian yang menyakitkan. Rasa nyeri dan ngilu Si-Chi bak hantaman telak ke ulu hati.
Lin Yi-Han tidak sempat menyaksikan karya yang ia tulis menggerakan generasi muda Taiwan untuk terjun dalam gerakan #metoo. Saat itu penyintas kekerasan seksual ramai-ramai menulis nama pelaku karena paham bahwa era pembungkaman harus segera diakhiri.
Baca juga:
Fang Si-Chi adalah Lin Yi-Han itu sendiri. Orang tua Yi-Han menyebut novel ini sebagai autobiografi. Maka seharusnya mereka juga menyadari, porsi orang tua dalam Fang Si-Chi’s First Love Paradise yang nyaris nihil. Keduanya absen dalam melindungi Si-Chi. Keduanya kabur ketika Si-Chi mulai kehilangan kesadaran. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Yi-Han ketika memandang orang tuanya?
Inilah bagian paling sulit dari membaca Fang Si-Chi: ceritanya berkelindan dengan kenyataan. Sulit untuk mencerna kesakitan macam apa yang dilalui Yi-Han ketika ia harus mereka-reka isi kepala pelaku ketika melakukan pelecehan, lantas menuliskannya dalam bentuk dialog.
Dalam konteks Indonesia, cerita Fang Si-Chi bagai pantulan air. Kita menemukan kisah serupa di sekolah, pesantren, gereja, kampus, dan di tempat-tempat yang sebagian orang menganggapnya ruang aman. Pelaku tidak jauh-jauh dari guru, dosen, pemuka agama—pendeknya, kelompok yang dianggap paling bermoral.
Fang Si-Chi’s First Love Paradise perlu dibaca bukan hanya karena kita mesti berduka atas apa yang menimpa tokoh utama dan penulisnya. Novel ini perlu dibaca karena seringkali fiksi punya cara yang lebih efisien untuk menjelaskan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata. (*)
Editor: Kukuh Basuki