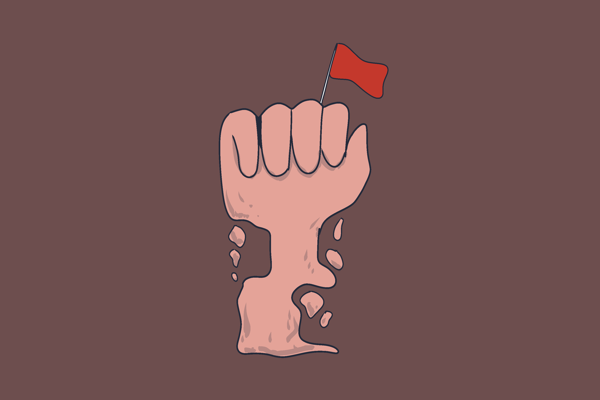Meski perayaan resminya baru terjadi pada 28 Oktober, peringatan Sumpah Pemuda agaknya telah dilakukan lebih awal, yakni pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Bila pada 28 Oktober peringatan sumpah pemuda dilakukan dengan semacam ritual kosong, yaitu pamflet, foto serta ucapan diberbagai sudut ruang publik, peristiwa pada akhir Agustus hingga awal September lalu dilakukan dengan cara yang lebih mencerminkan gairah orang muda: semangat kritis dan pemberontakan emansipatif. Dan entah disengaja atau tidak, sejarah berulang, titik pusat perayaan terjadi di tempat yang sama, Kwitang. Meski demikian, perayaan tersebut tidak diganjar dengan pemenuhan tuntutan, tetapi hadiah getir berupa penahanan, kekerasan, pemidanaan, hingga kematian.
Demonstrasi dengan tuntutan 17+8 lalu, menjadi simbol betapa distribusi keadilan yang seharusnya menjangkau tiap pintu ruamh warga negara, malah tersumbat hanya pada “meja” segelintir penguasa. Pasca demo Agustus 2025, ada 12 aktivis yang ditahan sebagai tersangka penghasutan dan dua orang dilaporkan masih hilang. Selain itu, 10 warga negara meregang nyawa. Jumlah tersebut belum termasuk ekses demonstrasi setahun terakhir, dimana 4.453 korban ditangkap, 744 korban menanggung kekerasan fisik, dan 341 orang menjadi korban penggunaan water canon dan gas air mata (Amnesty International, 2025). Tiap kali massa turun ke jalan, kita melihat ulangan tragedi yang sama, semangat revolusioner yang dibalas dengan kekerasan represif.
Baca juga:
Amat sukar untuk memandang rangkaian pertistiwa yang terjadi sebagai tragedi, malah lebih nampak sebagai pola yang direplikasi. Mengapa fenomena yang sama berulang? Apakah realitas tersebut memang menyingkap betapa bebalnya pemerintah? Atau justru gerakan masyarakat sipil memang gagal?
Kebebalan Pemerintah
Negara kerap melabeli demonstrasi dengan tuduhan tak masuk akal: didalangi asing hingga dimodali koruptor. Pemerintah, dalam logika ini, tidak lagi berperan sebagai fasilitator deliberasi dalam ruang demokrasi, melainkan penjaga ketertiban semu. Ketika ribuan mahasiswa, buruh, petani, dan pelajar turun ke jalan, aparat sering kali menanggapinya bukan dengan kehendak untuk mendengar, melainkan dengan tameng dan bedil. Kekerasan telah bertransformasi menjadi bahasa politik yang paling mudah dipahami oleh kekuasaan yang enggan berdialog.
Kebebalan pemerintah terlihat bukan hanya dari tindakan represif, tetapi juga dari kegagalannya membaca arah zaman. Di tengah era keterbukaan informasi—ketika kesadaran dan solidaritas warga tumbuh lintas kelas dan generasi—pemerintah masih beroperasi dengan logika feodal dan militeristik. Kekuasaan yang seharusnya beradaptasi dengan partisipasi, malah meneguhkan diri lewat represi dan eksklusi.
Temuan Global State of Democracy dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2021) menunjukan bahwa 165 negara di dunia, termasuk Indonesia demokrasi mengalami penurunan kualitas demokrasi sebesar 80% sejak 2015. Dalam laporan “Democracy Index 2023: Age of Conflict” yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU), skor demokrasi Indonesia turun dua tingkat dari tahun 6,71 pada 2022, ke 6,53 pada 2024. Temuan tersebut menguatkan kecenderungan bebal pemerintah untuk mengabaikan partisipasi dan deliberasi dalam demokrasi.
Refleksi terhadap Gerakan Sipil
Menyalahkan pemerintah saja terlalu mudah, bahkan cenderung malas. Dalam politik demokratis, kekuasaan yang bebal sering bertahan justru karena lemahnya gerakan yang mengawalnya. Masyarakat sipil hari ini tengah mengalami krisis orientasi. Gerakan rakyat yang dulu menjadi kekuatan moral kini terjebak dalam fragmentasi, personalisasi, dan kehilangan daya tekan terhadap kekuasaan.
Jika mencermati berbagai demonstrasi terakhir, akan nampak penuh gairah, tetapi kosong dalam tujuan dan arah. Memang ada narasi besar yang memayungi tuntutan, tetapi tak ada strategi jangka panjang yang menjembatani gerakan jalanan menjadi transformasi kebijakan. Gerakan sipil yang seharusnya menjadi “penyeimbang negara” justru kerap terjebak dalam romantisme perlawanan.
Baca juga:
Sebagian aktivis larut dalam dunia maya, mengira tanda pagar adalah bentuk perjuangan. Sebagian lain sibuk dengan identitas dan simbol kelompoknya masing-masing. Akibatnya, kritik kehilangan daya gigit. Gerakan kehilangan legitimasi. Di titik ini, kekuasaan yang bebal tak perlu terlalu cerdas, cukup menunggu masyarakat sipil melemah dengan sendirinya.
Dalam konteks ini, pemerintah yang bebal dan masyarakat sipil yang gagal adalah dua sisi dari koin yang sama. Kebebalan kekuasaan tumbuh di tanah tandus tanpa jamahan oposisi moral. Ketika gerakan sosial gagal menawarkan alternatif yang rasional dan konsisten, kekuasaan merasa berhak melanjutkan ketulian politiknya. Maka tragedi kekerasan terhadap demonstran bukan sekadar akibat aparat yang brutal, tapi juga hasil dari ekosistem demokrasi yang pincang, rakyat yang lelah, aktivis yang tercerai, dan negara yang abai.
Reformulasi Gerakan
Kita perlu mereposisi cara pandang terhadap demonstrasi. Demonstrasi terlarang berhenti sebagai ritual heroik musiman yang dibayar dengan kriminalisasi dan represi. Demonstrasi harus kembali dipahami sebagai bentuk komunikasi politik yang rasional dan terencana, bukan sekadar “melawan,” tetapi juga “mengartikulasikan,” mengubah energi moral menjadi energi politik.
Gerakan rakyat perlu kembali membangun infrastruktur intelektualnya yaitu riset, pendidikan politik, jaringan lintas sektor, serta kemampuan membingkai isu dalam bahasa publik. Gerakan tanpa basis pengetahuan akan mudah dikooptasi oleh kepentingan sesaat. Di sinilah pentingnya “kecerdasan gerakan”, yakni kemampuan mengubah protes menjadi program, dan tuntutan menjadi kebijakan.
Sebaliknya, pemerintah mesti belajar untuk tidak hanya mendengarkan gerakan, tetapi juga mengantisipasi demonstrasi dengan keadilan yang mewujud dalam regulasi. Kekuasaan yang takut pada kritik adalah kekuasaan yang tidak percaya pada kapasitasnya sendiri. Pemerintah seharusnya merawat kritik, menjadikannya sarana untuk mengoreksi arah kebijakan. Dalam demokrasi yang sehat, demonstrasi adalah tanda vitalitas politik.
Mungkin benar bahwa setiap zaman punya bentuk pemberontakannya sendiri. Jika generasi 1928 melawan penjajahan, generasi kini melawan penindasan dalam bentuk yang lain, yakni oligarki, ketimpangan, dan manipulasi hukum. Tetapi sebagaimana para pemuda di Kwitang hampir seabad lalu menegaskan “bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu,” generasi kini perlu menegaskan sumpah barunya: bertumpah ide yang sama, berbangsa kesadaran yang sama, dan berbahasa keadilan yang sama.
Perjuangan politik hari ini bukan lagi soal merebut kekuasaan, melainkan mengembalikan akal sehat publik. Dan untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat sipil mesti mengajukan tanya. Bagi pemerintah: Sejauh mana masih memerintah untuk rakyat, bukannya atas nama rakyat? Sedangkan masyarakat bagi masyarakat sipil: sejauh mana kita benar-benar berjuang, bukan sekadar mengutuk?
Dan pada akhirnya, sejarah bukanlah deretan peristiwa besar, melainkan jejak kecil yang dibiarkan manusia ketika melangkah dengan nuraninya. Mungkin demonstrasi, dengan segala luka dan kebisuan yang ditinggalkannya, adalah salah satu jejak itu. Menjadi tanda bahwa bangsa ini masih hidup, masih mampu marah, masih sanggup berharap.
Sebab yang paling berbahaya bukanlah negara yang menindas, tetapi masyarakat yang berhenti peduli. Ketika tak ada lagi orang yang mau berteriak, maka kekuasaan tak perlu lagi menembak. Ia cukup diam, dan kita pun akan lelap perlahan dalam kepatuhan yang sunyi. (*)
Editor: Kukuh Basuki